MK Didesak Tolak Permohonan Pengujian UU yang Longgarkan Remisi bagi Napi Korupsi
Tim Advokasi ini mendesak MK menolak permohonan pengujian UU yang melonggarkan syarat pemberian remisi bagi napi korupsi.
WARTA KOTA, PALMERAH -- Tim Advokasi Pro-Pembatasan Remisi untuk Koruptor meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan pengujian undang-undang (UU) yang melonggarkan syarat pemberian remisi bagi naripadana korupsi.
Tim Advokasi yang dibentuk oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu mencatat, sejumlah terpidana kasus korupsi sedang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Ketiga lembaga itu menilai pengujian terhadap Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagai siasat untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman yang sedang dijalani.
Dalam argumentasinya, pemohon menilai bahwa remisi merupakan hak seluruh narapidana (Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995) namun pada kenyataannya para pemohon yang merupakan napikasus korupsi hingga kini tidak mendapatkan hak tersebut, padahal menurutnya telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Sehingga menilai hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran atas hak asasi manusia.
"Upaya yang dilakukan oleh para pemohon dapat dilihat sebagai siasat untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman," kata Erasmus Napitupulu, peneliti ICJR akhir pekan ini.
Alasannya, menurut Erasmus, selain argumentasinya prematur, pemohon adalah napi korupsi yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setidaknya, katanya lebih lanjut, ada enam alasan mengapa MK harus menolak pengujian yang diajukan pemohon.
Pertama, terpidana kasus korupsi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Meskipun disebut sebagai hak napi namun ada tata cara dan syarat yang mengatur pemberian remisi.
PP 99/2012, tegasnya, mengamanatkan syarat tambahan bagi narpidana kasus korupsi yaitu menyandang status Justice Collaborator dan telah membayar denda / uang pengganti. Syarat ini tidaklah dapat dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU 12/1995.
Kedua, pengetatan remisi adalah kebijakan hukum pemerintah. Pengetatan remisi dalam PP 99/2012 merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka pemerintah. UU 12/1995 dalam Pasal 14 ayat (2) mengamanatkan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
"Ini berarti bagaimana remisi diberikan merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah," ujarnya.
Ketiga, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 51 P/HUM/2013 dan 63 P/HUM/2015 menguatkan keberadaan PP 99/2012. MA melalui dua putusannya menilai bahwa pengetatan remisi bagi napikorupsi bukan merupakan pelanggaran HAM, melainkan konsekuensi logis dari nilai atau bobot kejahatan yang memiliki dampak luar biasa.
Keempat, pengetatan remisi sejalan dengan semangat United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC). Bahwa dalam rekomendasi peninjau UNCAC menilai dalam praktiknya, aturan hukum Indonesia belum memadai untuk mengakomodasi pengaturan yang berkaitan dengan remisi atau pembebasan beryarat.
Peninjau UNCAC juga merekomendasikan pemerintah untuk menjadikan kejahatan korupsi sebagai alasan pemberat dalam pertimbangan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat.
Hal ini neburut ICW, ICJR dan PBHI sejalan dengan butir ke-5 Article 30 UNCAC yang berbunyi: “Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences”
Kelima, pengetatan remisi juga sejalan prinsip dalam Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners Tahun 1955 dan UU 12/1995. Bahwa Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners Tahun 1955 angka 70 menyebutkan bahwa diberikannya hak remisi kepada narapidana harus dilakukan di setiap lapas dengan disesuaikan dalam kelas-kelas napiyang berbeda dan cara-cara perlakuan pembinaan yang berbeda.


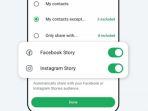






![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)




